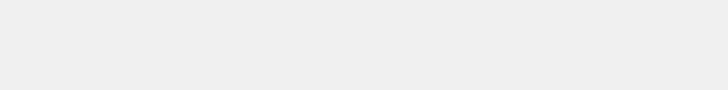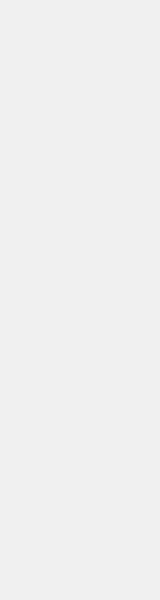:strip_icc()/kly-media-production/medias/2704251/original/000193900_1547530828-bendera_AS.jpg)
Pemerintah Amerika Serikat pada akhir tahun 2020 mengajukan rencana program percontohan yang mensyaratkan jaminan keuangan hingga $15.000 (sekitar Rp 233 juta) dari para pelancong bisnis dan turis dari 23 negara dengan tingkat 'overstay' visa B1/B2 (bisnis/turis) yang tinggi, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran di komunitas internasional. Program ini, yang seharusnya berlaku pada 24 Desember 2020, dirancang untuk menguji kelayakan pengumpulan jaminan dari pemohon visa dan dikelola oleh Kedutaan Besar dan Konsulat AS di negara-negara yang masuk daftar tersebut. Sementara itu, Indonesia, yang sebelumnya sempat masuk dalam daftar pantauan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS karena tingkat 'overstay' yang relatif tinggi, tidak termasuk dalam daftar 23 negara yang diwajibkan membayar jaminan tersebut.
Rencana program ini diumumkan melalui Federal Register pada November 2020 oleh Departemen Luar Negeri AS. Ini dirancang untuk menargetkan pemohon visa B1/B2 dari negara-negara dengan tingkat 'overstay' lebih dari 10 persen pada tahun fiskal 2019, yang mencakup negara-negara di Afrika dan Asia. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka 'overstay' dengan memberikan insentif finansial bagi pemegang visa untuk kembali ke negara asal mereka tepat waktu. Dokumen resmi menyatakan bahwa program percontohan tersebut akan berlangsung selama enam bulan dan dapat diperbarui atau diperluas setelah evaluasi.
Pengecualian Indonesia dari daftar negara yang diwajibkan membayar jaminan ini menarik perhatian, mengingat data sebelumnya yang menunjukkan tingkat 'overstay' yang signifikan dari warga negara Indonesia di AS. Pada tahun 2018, misalnya, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS melaporkan bahwa sekitar 6.000 warga negara Indonesia yang masuk ke AS dengan visa turis atau bisnis melampaui batas waktu izin tinggal mereka. Meskipun demikian, pemerintah AS tidak memasukkan Indonesia dalam program jaminan tersebut. Kebijakan ini menekankan kompleksitas hubungan bilateral dan pertimbangan diplomatik dalam keputusan imigrasi AS, serta potensi upaya kolaboratif antara kedua negara dalam mengelola isu imigrasi.
Implikasi dari kebijakan jaminan visa ini sangat signifikan bagi negara-negara yang termasuk dalam daftar tersebut. Beban finansial yang dikenakan melalui jaminan $5.000 hingga $15.000 per orang dapat menjadi penghalang besar bagi banyak individu yang ingin mengunjungi AS untuk tujuan bisnis atau pariwisata. Kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah pengunjung dari negara-negara tersebut, berdampak pada sektor pariwisata dan perdagangan. Selain itu, langkah tersebut dapat dilihat sebagai tindakan diskriminatif oleh negara-negara yang ditargetkan, yang berpotensi memicu ketegangan diplomatik dan memengaruhi persepsi global terhadap kebijakan imigrasi AS. Pakar imigrasi menyatakan bahwa meskipun tujuan utamanya adalah mengurangi 'overstay', metode ini bisa jadi terlalu memberatkan dan tidak proporsional, serta dapat menimbulkan hambatan ekonomi dan hubungan antarnegara.
Latar belakang kebijakan ini dapat ditelusuri pada upaya administrasi sebelumnya untuk memperketat kontrol imigrasi dan mengurangi jumlah imigran ilegal dan pelanggar visa. Meskipun program percontohan ini diajukan pada akhir masa jabatan pemerintahan sebelumnya, diskusi tentang efektivitas dan keadilannya terus berlanjut. Pertanyaan mengenai apakah program ini akan benar-benar efektif dalam jangka panjang tanpa menimbulkan konsekuensi negatif yang lebih besar masih menjadi fokus perdebatan. Sementara itu, bagi Indonesia, pengecualian dari daftar tersebut mencerminkan dinamika hubungan diplomatik yang berbeda atau mungkin pengakuan atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah 'overstay' atau faktor-faktor lain dalam penilaian risiko Departemen Luar Negeri AS.